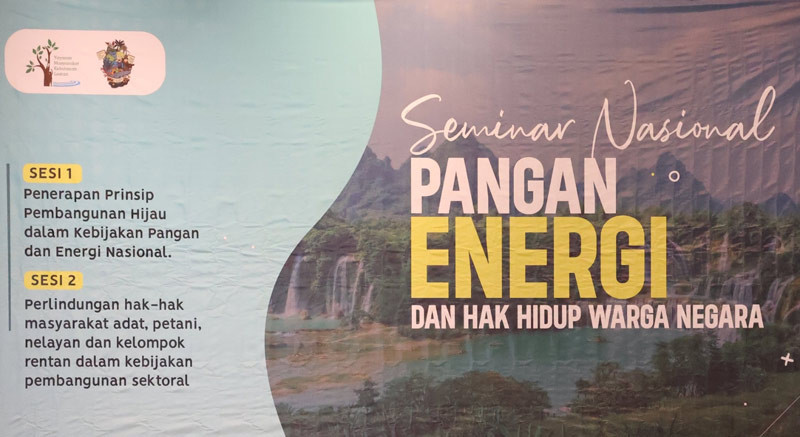Darilaut – Ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia masih sangat tajam. Lebih dari 61,3% petani kini berstatus gurem, yakni hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar. Artinya, enam dari sepuluh petani di pedesaan hidup di atas tanah yang tidak mencukupi untuk bertani layak.
Hal ini berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang disampaikan pada Seminar Nasional Pangan dan Energi: Perlindungan Hak-hak masyarakat adat, Petani, Nelayan dan Kelompok Rentan Dalam Kebijakan Pembangunan Sektoral, di Jakarta 11 November 2025
Satu dekade terakhir, jumlah petani gurem meningkat 2,63 juta orang, atau sekitar 263 ribu orang setiap tahun, sementara lahan pertanian justru berkurang 2,63 juta hektar akibat konversi untuk industri, perkebunan, tambang, dan infrastruktur.
“Ada 25.000 desa yang masih diklaim kawasan hutan; keluarkan mereka dari status itu agar bisa hidup dan bertani dengan adil. 11 tahun terakhir, hanya 0,024% konflik agraria yang benar-benar diselesaikan oleh KLHK ini bukti betapa lambatnya negara,” ujar Roni Septian dari Konsorsium Pembaruan Agraria, dalam seminar.
Situasi ini menunjukkan bahwa ketimpangan agraria bukan sekadar masalah kepemilikan tanah, melainkan juga persoalan keadilan sosial dan hak hidup.
Ketika lahan semakin sempit, jumlah buruh tani meningkat, dan petani tidak mampu lagi memproduksi pangan secara mandiri, maka kedaulatan pangan bangsa pun melemah.
Roni menyoroti bahwa pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto kembali menempatkan reforma agraria dalam Asta Cita poin 2 dan 6, yakni untuk mencapai swasembada pangan dan pemerataan ekonomi.
Namun Roni mengingatkan Reforma agraria tidak boleh menjadi pengulangan dari program sebelumnya yang berhenti di tataran janji.
Roni menjelaskan ada lebih dari satu juta hektar wilayah garapan petani yang diklaim sebagai kawasan hutan, perkebunan, atau pertambangan, namun tidak pernah mendapat dukungan infrastruktur maupun kebijakan dari negara.
Bahkan di banyak desa yang masih berstatus kawasan hutan, kepala desa yang menggunakan dana desa untuk membangun jalan justru ditangkap, karena dianggap membangun di “tanah negara”.
Dari hasil pemetaan KPA, terdapat 25.000 desa yang masih diklaim berada di dalam kawasan hutan, baik seluruhnya maupun sebagian. Roni menyerukan kepada Kementerian LHK agar segera mengeluarkan SK bersama untuk melepaskan 25.000 desa ini dari klaim kawasan hutan, sehingga bisa masuk dalam program reforma agraria sejati.
“Petani menguasai, memproduksi, dan mengontrol hasil pertaniannya sendiri itulah reforma agraria sejati. Reforma agraria sejati butuh lembaga kuat di bawah Presiden, yang bisa mengeksekusi dan membatalkan izin tumpang tindih lintas sektor,” ujarnya.
Namun, KPA tidak hanya berhenti pada kritik. Dia menjelaskan bagaimana gerakan rakyat sendiri mengambil inisiatif di lapangan melalui program DAMARA (Dapur Mandiri Reforma Agraria).
DAMARA merupakan model reforma agraria dari bawah, di mana rakyat mengorganisir diri, menguasai dan mengelola tanah secara kolektif, serta membangun sistem produksi dan distribusi yang mandiri.
Melalui DAMARA, masyarakat di Indramayu, Majalengka, dan Cilacap berhasil membangun alat-alat pertanian sendiri secara swadaya, mengelola pabrik penggilingan gabah, dan menstabilkan harga beras. Gerakan rakyat melalui DAMARA membuktikan bahwa reforma agraria bisa dijalankan tanpa menunggu kebijakan pemerintah.”
“Petani membeli dan menjual hasil panen dengan harga yang adil,” kata Roni.
Roni kemudian menyampaikan kisah di Cilacap, di mana petani membangun jalan sepanjang 40 kilometer secara gotong royong, tanpa bantuan pemerintah. Bahkan Menteri LHK yang datang ke lokasi mengira wilayah itu kawasan hutan, padahal sudah menjadi sawah produktif selama puluhan tahun.
“Tidak ada satu pun pohon di sana,” kata Roni, “tapi masih disebut kawasan hutan. Ini bukti absurditas birokrasi yang perlu diakhiri.”