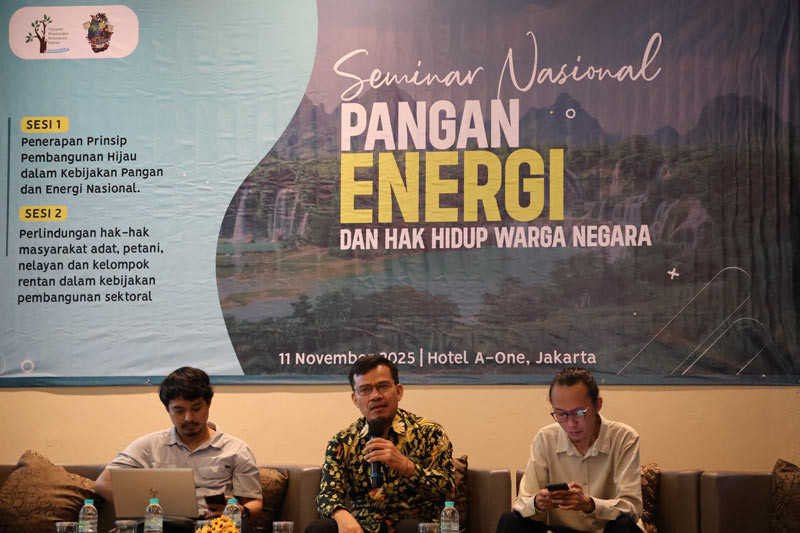Darilaut – Pemerintahan Presiden Prabowo telah menetapkan Misi lima tahun pembangunan dalam masa pemerintahannya yang dikenal dengan Asta Cita. Berlandaskan pada Prinsip Ekonomi Pancasila, Asta Cita menempatkan ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia sebagai pilar utama pembangunan berlandaskan religiositas kehidupan berbangsa dan persatuan nasional yang kuat.
Cita kedua adalah memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
Pemerintahan Presiden Prabowo tampak lebih memberikan prioritas pada pelaksanaan Cita kedua yang justru menimbulkan pertanyaan serius tentang perhatian Pemerintah pada pelaksanaan Cita pertama. Upaya mendorong swasembada pangan dan kemandirian energi dilakukan melalui ekspansi berbasis lahan skala sangat luas yang dikemas dalam istilah Proyek Strategis Nasional.
Upaya ini telah menimbulkan masalah sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan bagi masyarakat di berbagai tempat di mana proyek energi dan pangan skala besar di laksanakan. Dalam rentang waktu singkat tanah-tanah adat dan lahan-lahan komunitas lokal serta hutan alam di berbagai lokasi Proyek Strategis Nasional beralih menjadi lokasi proyek.
Situasi tersebut mengancam kelangsungan hidup masyarakat adat dan komunitas lokal. Bahkan tak sedikit korban nyawa dan harta benda serta disorientasi sosial yang parah di komunitas-komunitas masyarakat adat dan lokal. Perlindungan bagi keselamatan hidup dan hak-hak dasar mereka menjadi sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan oleh negara. Masyarakat sendiri perlu mengembangkan inisiatif-inisiatif perlindungan dan penyelamatan diri dan hak-hak mereka.
Saurlin P. Siagian, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, mengatakan, pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah harus mengakomodir dan melindungi kehidupan dan hak-hak masyarakat.
“Meskipun menghadapi sejumlah tantangan, Komnas HAM bertekad untuk tetap menjalankan perannya secara efektif agar dapat beresonansi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Saurlin pada seminar nasional yang diadakan oleh Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari bertema: Pangan, Energi dan Hak Hidup Warga Negara dengan Sub-tema Penerapan Prinsip Pembangunan Hijau dalam Kebijakan Pangan dan energi Nasioinal, di Jakarta, pada Selasa (11/11).
Saurlin menilai salah satu isu utama yang menjadi fokus perhatian Komnas HAM adalah Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster Proyek Strategis Nasional.
“Kami telah menyampaikan pandangan kritis kami terkait UU ini. Dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), di mana OMS mengajukan gugatan, terungkap bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja dilakukan secara terburu-buru. Selain itu, terdapat catatan bahwa pengadministrasian proyek strategis yang seharusnya tidak diatur pada level undang-undang,” katanya.
Terkait dengan berbagai konflik dan sengketa yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, Komnas juga mencatat adanya peningkatan kasus kriminalisasi terhadap pejuang HAM dan masyarakat. “Upaya penegakan HAM di era ini semakin sulit,” ujar Saurlin seraya menambahkan orang yang memperjuangkan haknya tidak seharusnya dikriminalisasi. Perlu penguatan upaya perlindungan bagi individu dan kelompok masyarakat adat yang memperjuangkan hak-hak mereka.
Komnas HAM telah mengeluarkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) yang ditetapkan pada 2024 melalui rapat paripurna yang melibatkan partisipasi luas dari berbagai universitas, organisasi masyarakat sipil, serta para ahli dari Komnas HAM.
“Ini merupakan salah satu langkah menguatkan upaya perlindungan,” ujar Saurlin.
“Komitmen Indonesia terhadap perlindungan masyarakat adat berakar pada Konstitusi, dan diperkuat melalui ratifikasi berbagai konvensi internasional, mulai dari Konvensi ILO, CERD, hingga CEDAW. SNP ini selaras dengan komitmen global tersebut.”
Transisi Energi dan Swasembada Pangan
Semua tujuan dan target pembangunan yang mulia ini hanya mungkin tercapai bila kedaulatan Indonesia tetap terjaga utuh dan kukuh. Pangan dan Energi adalah dua sektor paling strategis bagi kelangsungan hidup berbangsa dan kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Dua sektor ini pula yang menjadi kunci kedaulatan setiap negeri.
Pada sektor energi pemerintah ingin mewujudkan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sementara di sektor pangan pemerintah menegaskan pencapaian swasembada pangan dalam waktu sesingkat mungkin.
Namun upaya ambisius ini memperlihatkan dampak tragis bagi masyarakat di kampung-kampung di lokasi proyek strategis nasional dalam dua sektor ini.
Terjadi perluasan zona pengorbanan (sacrifice zones) akibat watak ekstraktif dari ekspansi industri energi yang dibalut slogan ‘transisi energi’. Oleh karena itu, skema ini justru dinilai sebagai bentuk ekspansi perusahaan energi untuk memperkaya investor, bukan upaya nyata pelestarian lingkungan dalam rangka pembangunan hijau.
Muhammad Jamil Kepala Divisi Hukum dan Kebijakan JATAM menyoroti daya rusak yang terjadi atas nama transisi energi, terutama setelah tujuh tahun beroperasinya PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), yang dia sebut sebagai “Rupa Perampokan dan Penaklukan Alam Berkedok Transisi Energi.”
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa transisi energi tidak membawa perubahan, bahkan cenderung memperburuk kondisi lingkungan melalui perluasan tambang untuk produksi baterai listrik.
Di Desa Kawasi, Pulau Obi, Maluku Utara, sungai dan air laut telah tercemar lumpur tambang yang dipindahkan ke belakang gunung. Selain itu, terdapat upaya penghapusan administratif kampung. Terjadi penurunan kualitas kesehatan masyarakat di Weda Utara dan Weda Tengah. Warga Halmahera mengalami perampasan air di tengah kondisi pencemaran yang parah. Hasil uji laboratorium terbaru (2024) terhadap Sungai Sagea-Boki Mauru dan Sungai Kobe mengonfirmasi adanya kandungan BOD dan COD yang mengandung nikel.
Proyek transisi energi ini banyak terjadi di pulau-pulau kecil (pulau di bawah 2.000 km²) yang seharusnya dilindungi. Praktik penambangan ini juga memangsa lahan pertanian dan mengancam ketahanan pangan.
Ironisnya, kata Jamil, transisi energi justru memangsa pulau-pulau kecil di bawah 2.000 km² yang seharusnya dilindungi dari tambang minerba. Ini bukan hanya krisis lingkungan, tetapi ancaman langsung terhadap lahan pertanian dan ketahanan pangan nasional. Filosofi energi skala besar yang dianut negara ini sungguh aneh dan tidak berkelanjutan, terbukti dari kegagalan masif seperti MBG.
”Kami mendesak negara belajar dari masyarakat adat, yang sejak lama memikirkan pengelolaan sumber daya secara terkelola, dari hulu hingga ke hilir, tanpa mengorbankan alam,” kata Jamil pada sesi seminar.
Menurut Jamil model pambangunan di bidang energi yang berskala besar sulit dikelola secara selaras dengan semangat pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan. ”Sangat bermasalah,” ujar Jamil.
Berbeda dengan pendekatan tersebut, masyarakat adat menerapkan skala yang terkelola, memikirkan siklus sumber daya dari hulu hingga hilir. Bisa disimpulkan bahwa kerusakan bentang politik di Indonesia saat ini secara sistematis mengorbankan manusia dan alam.
“Pemerintah perlu belajar dari masyarakat mengenai skala yang terkelola,” kata Jamil.
“Transisi energi saat ini adalah ilusi percepatan. Pemerintah hanya bicara peningkatan nilai tambah, percepatan produksi, dan semakin besarnya skala tambang. Semakin besar skala tambang, semakin masif pula kerusakannya.”
Ancaman Pembela Lingkungan dan HAM
Praktik pelaksanaan proyek pembangunan berbasis sumber daya alam sering memakan korban individu dan masyarakat yang mempertahankan tanah dan wilayah kelola mereka. Hal ini bersumber dari pengabaian dan pelanggaran terhadap prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC).
Tanah-tanah dan hutan-hutan serta perairan diambil dengan cara-cara kekerasan, intimidasi dan manipulasi informasi.
Menyoroti realitas ini, Theo Reffelsen, Manajer Hukum dan Pembelaan WALHI menegaskan pelaksanaan prinsip FPIC bagian dari pelaksanaan Deklarasi PBB tentang Hak Atas Pembangunan.
“Persetujuan masyarakat tidak boleh diwarnai intimidasi atau trauma kekerasan”…. ”Kami tegaskan, pembangunan berkelanjutan hanya sah jika didasarkan pada ‘persetujuan bebas tanpa paksaan’ (FPIC), informasi yang akurat, dan hak penentuan nasib sendiri,” ujar Theo.
Sesuai Resolusi Komisi HAM PBB Nomor 77 Tahun 1993, penggusuran paksa dan segala bentuk tindakan tidak manusiawi yang menyertainya adalah pelanggaran HAM berat. Negara harus menghentikan praktik ini segera. Kami mencermati bahwa di lapangan, persetujuan sering didapat melalui paksaan, ancaman kriminalisasi, dan intimidasi, kata Theo.
Theo mengatakan dua hal dalam pembelaan bagi para pembela HAM dan hak atas lingkungan. Penting untuk mendorong pengakuan dan perlindungan bagi pembela lingkungan hidup dan hak asasi manusia dan perluasan konteks subjek yang termasuk dalam kategori pembela HAM dan lingkungan.
Dalam sejumlah kasus yang ditemui, Theo menjelaskan bahwa upaya pembelaan bagi subjek menghadapi kendala sempitnya cakupan definisi pembela HAM dan lingkungan.
Isu perlindungan Pembela Lingkungan dan Hak Asasi Manusia (PL-HAM) diperburuk oleh praktik penegak hukum yang secara struktural dan kultural bermasalah. WALHI mencatat adanya kecenderungan APH (Aparat Penegak Hukum) untuk menyalahkan PL-HAM, menuduh mereka berkontribusi pada konflik karena dianggap tidak bertanggung jawab.
Padahal, masalah utama terletak pada APH sendiri mengidentifikasi persoalan struktural, instrumental, dan budaya di kalangan APH. Mereka pada dasarnya mengetahui bahwa masyarakat adat sedang memperjuangkan hak-haknya. Namun, alih-alih melindungi, APH justru memfasilitasi terjadinya kriminalisasi terhadap para pejuang hak.
Menurut Theo, perlindungan Pembela HAM Lingkungan harus diperkuat melalui legislasi. Pengesahan segera UU Anti-SLAPP dan UU Partisipasi Publik adalah keharusan untuk memperluas subjek perlindungan dan menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif bagi mereka yang dikriminalisasi. Instrumen Hukum Acara Pidana dan Perdata harus mampu mendeteksi ‘motif yang tidak benar’ (improper motive) di balik gugatan dan tuntutan. Ini adalah kunci untuk menghentikan praktik kriminalisasi berkedok proses hukum terhadap para pejuang lingkungan.
Oleh karena itu, perbaikan mendesak dalam tubuh APH harus dilakukan. APH wajib memahami motif perjuangan yang dilakukan masyarakat adat agar anggaran negara tidak terbuang percuma, terutama dalam konteks menurunnya indeks demokrasi Indonesia.
Theo menekankan perlunya kerja sama yang kuat untuk menghadapi situasi ini, termasuk melalui upaya judicial review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster yang terkait Proyek Strategis Nasional (PSN), demi mempertahankan ruang hidup masyarakat. Kolaborasi lintas organisasi dan masyarakat harus terus dilakukan secara intensif dalam menangani kasus-kasus sengketa, karena terbukti bahwa kemenangan sekecil apapun hanya dapat dicapai melalui upaya kolaboratif.
“Bahwa kemenangan, meskipun kecil, hanya lahir dari kolaborasi intensif lintas organisasi dan masyarakat,” ujarnya.